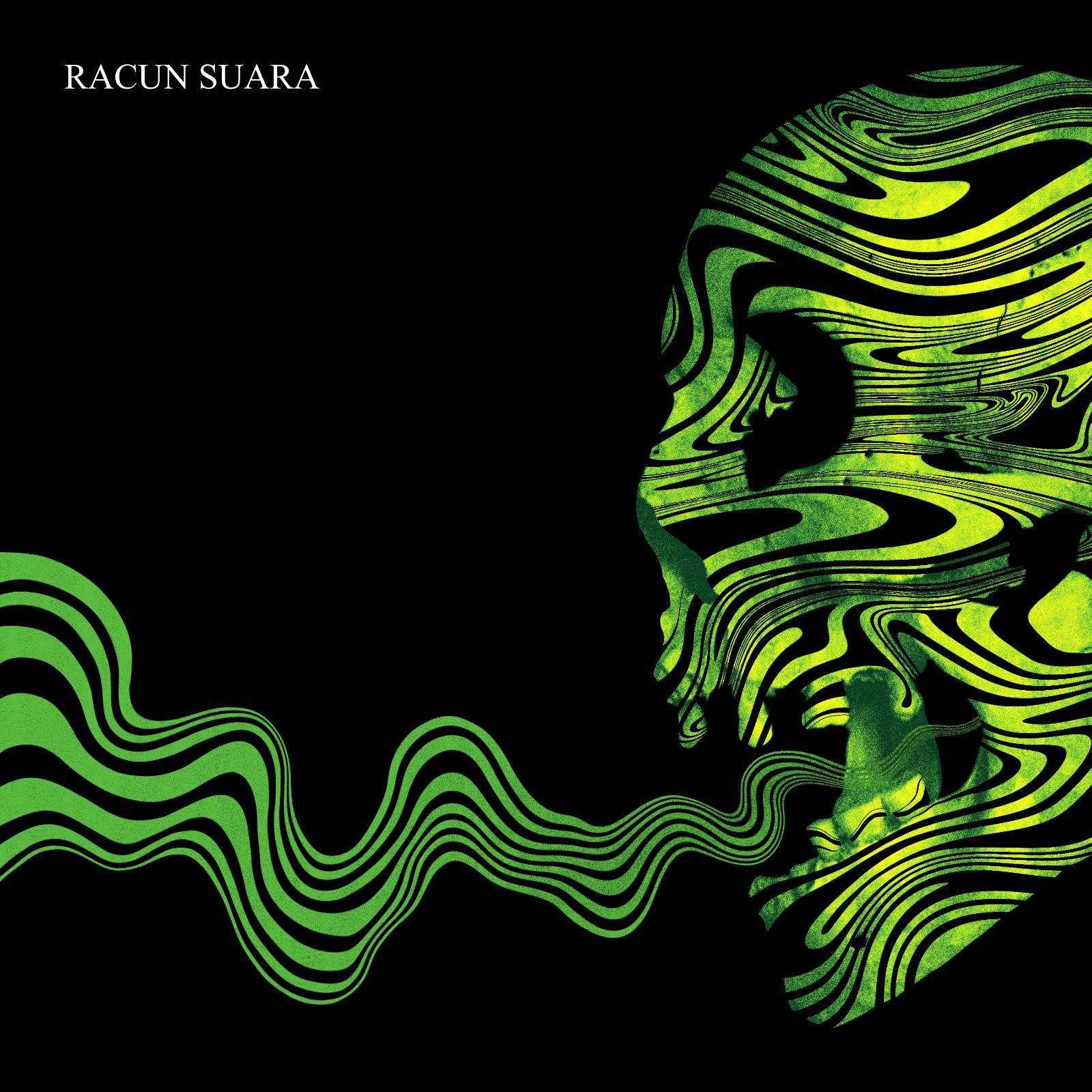Pada Kamis, 23 Oktober 2025 Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari puluhan advokat dan pegiat hak asasi manusia menjadi kuasa hukum dari delapan pemohon dalam permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi.
Permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk keberlanjutan gerakan masyarakat sipil untuk menolak perluasan jabatan militer di ranah sipil, impunitas TNI, dan perpanjangan masa pensiun jenderal TNI yang berakibat buruk bagi organisasi TNI itu sendiri. Undang-undang TNI tidak hanya mengabaikan partisipasi publik, tetapi juga memperkuat pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil.
Adapun Para Pemohon dalam Permohonan Uji Materil tersebut terdiri dari lima organisasi yang aktif melakukan kerja advokasi HAM dan demokrasi serta aktif mendorong reformasi sektor keamanan khususnya reformasi TNI, yakni Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan LBH APIK Jakarta. Selain pemohon organisasi terdapat juga tiga pemohon perseorangan, yakni: Ikhsan Yosarie, dosen sekaligus peneliti bidang pertahanan SETARA Institute. Dua pemohon lainnya ialah Mahasiswa UGM atas nama M. Adli Wafi dan M. Kevin Setio Haryanto yang sampai saat ini aktif melakukan kritik dan monitoring yang berkaitan dengan reformasi TNI.
Koalisi memandang UU TNI mengandung banyak permasalahan mulai dari segi pembentukan hingga substansi yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, permohonan ini menyasar pasal-pasal bermasalah di dalam UU TNI. *Pertama*, adanya pelanggaran prinsip kebebasan sipil dan kepastian hukum. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU TNI memberi kewenangan kepada TNI untuk “membantu mengatasi pemogokan dan konflik komunal” dalam operasi militer selain perang. Ketentuan ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak untuk melakukan pemogokan diakui sebagai bagian dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi dan Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948, yang telah diratifikasi Indonesia. Pelibatan militer dalam menghadapi pemogokan pekerja berarti menempatkan tindakan sipil yang sah sebagai ancaman keamanan negara. Selain itu, frasa “konflik komunal” dalam pasal tersebut bersifat multitafsir dan karet, karena tidak dijelaskan batasan hukumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum _(rechtsonzekerheid)_
sebagaimana dilarang oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan membuka peluang penyalahgunaan kekuatan bersenjata dalam urusan yang seharusnya ditangani aparat sipil dan hukum. Lebih lanjut, karetnya definisi dan ruang lingkup dari frasa “membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber” yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15, akan membuka ruang keterlibatan militer dalam urusan dan pengelolaan ancaman keamanan siber, khususnya yang berkaitan dengan ancaman yang mencakup aspek teknis keamanan siber, penegakan hukum kejahatan siber, dan aspek lainnya yang masuk kualifikasi keamanan sipil, yang bukan merupakan bagian dari tugas pokok TNI.
*Kedua*, peniadaan fungsi pengawasan DPR dalam operasi militer. Salah satu ketentuan yang diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2025 adalah ketentuan Pasal 7 ayat (4) yang mendelegasikan pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) kepada Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, tanpa melibatkan DPR. Padahal, konstitusi secara tegas mengatur bahwa setiap pengerahan kekuatan militer harus melalui keputusan politik negara (Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945). Dengan pendelegasian tersebut, fungsi _checks and balances_ DPR terhadap Presiden sebagai panglima tertinggi TNI menjadi terhapus. Hal ini berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan menjauhkan mekanisme akuntabilitas sipil terhadap militer, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi konstitusional. Koalisi menilai pengaturan ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip supremasi sipil yang telah menjadi fondasi utama demokrasi pasca reformasi 1998.
*Ketiga*, pelanggaran prinsip supremasi sipil dan pemisahan fungsi sipil-militer. Pasal 47 ayat (1) UU TNI memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan pada lembaga-lembaga sipil seperti Kesekretariatan Presiden, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kejaksaan RI. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945, serta TAP MPR No. VII/MPR/2000, yang menegaskan bahwa anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Ketentuan ini menandai kemunduran serius reformasi TNI dengan melegalisasi secara ugal-ugalan Dwifungsi TNI. Hal ini tidak hanya berbahaya bagi birokrasi sipil, tetapi juga terhadap profesionalisme militer itu sendiri, karena menciptakan tumpang tindih kewenangan, serta melemahkan independensi lembaga penegak hukum dan pemerintahan sipil.
*Keempat*, diskriminasi dan ketidakadilan struktural di tubuh TNI dengan diperpanjangnya usia pensiun para jenderal. Pasal 53 UU TNI memperpanjang usia pensiun perwira tinggi hingga 63 tahun dengan kemungkinan perpanjangan dua kali. Perubahan ini menciptakan ketimpangan karier internal _(career logjam)_ karena memperlambat regenerasi dan mempersempit peluang perwira muda untuk promosi jabatan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada stagnasi struktural, tetapi juga melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Selain itu, perpanjangan usia pensiun tanpa dasar kebutuhan objektif organisasi menimbulkan diskriminasi vertikal antara perwira tinggi dan jenjang lainnya, serta menambah beban anggaran pertahanan tanpa memperkuat profesionalitas TNI. Koalisi menilai pasal ini memperkuat feodalisme internal militer dan mengancam efektivitas struktur komando.
*Kelima*, mandeknya reformasi peradilan militer. Pasal 74 UU TNI menunda penerapan Pasal 65 UU TNI, yang menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada peradilan umum untuk perkara pidana umum. Penundaan tersebut menyebabkan sistem peradilan militer masih memiliki kewenangan absolut atas seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk tindak pidana umum seperti pembunuhan, korupsi, atau kekerasan terhadap warga sipil. Kondisi ini menimbulkan impunitas dan pelanggaran terhadap prinsip _equality before the law_, serta melanggar Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kesamaan di hadapan hukum. Dengan tetap berlakunya UU Peradilan Militer 1997, prajurit TNI masih dapat diadili di bawah sistem internal militer, sehingga tidak ada jaminan independensi dan transparansi peradilan. Koalisi menilai hal ini sebagai bentuk kegagalan negara dalam melaksanakan amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang menghendaki reformasi total peradilan militer.
Selain persoalan substansial dalam pasal-pasal di atas, eksistensi UU TNI juga menunjukkan ketidakseriusan politik pemerintah dan DPR dalam melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan. Pasal-pasal bermasalah tersebut menunjukkan upaya rekonsolidasi kekuatan militer dengan memanipulasi hukum.
*Jakarta, 23 Oktober 2025*
Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan
(Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, Centra Initiative, ICW, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), BEM SI, De Jure, Raksha Initiative, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Medan).
Narahubung:
1. Ardi Manto Adiputra (Imparsial)
2. Arif Maulana (YLBHI)
3. Fadhil Alfathan (LBH Jakarta)
4. Andrie Yunus (KontraS)

KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan