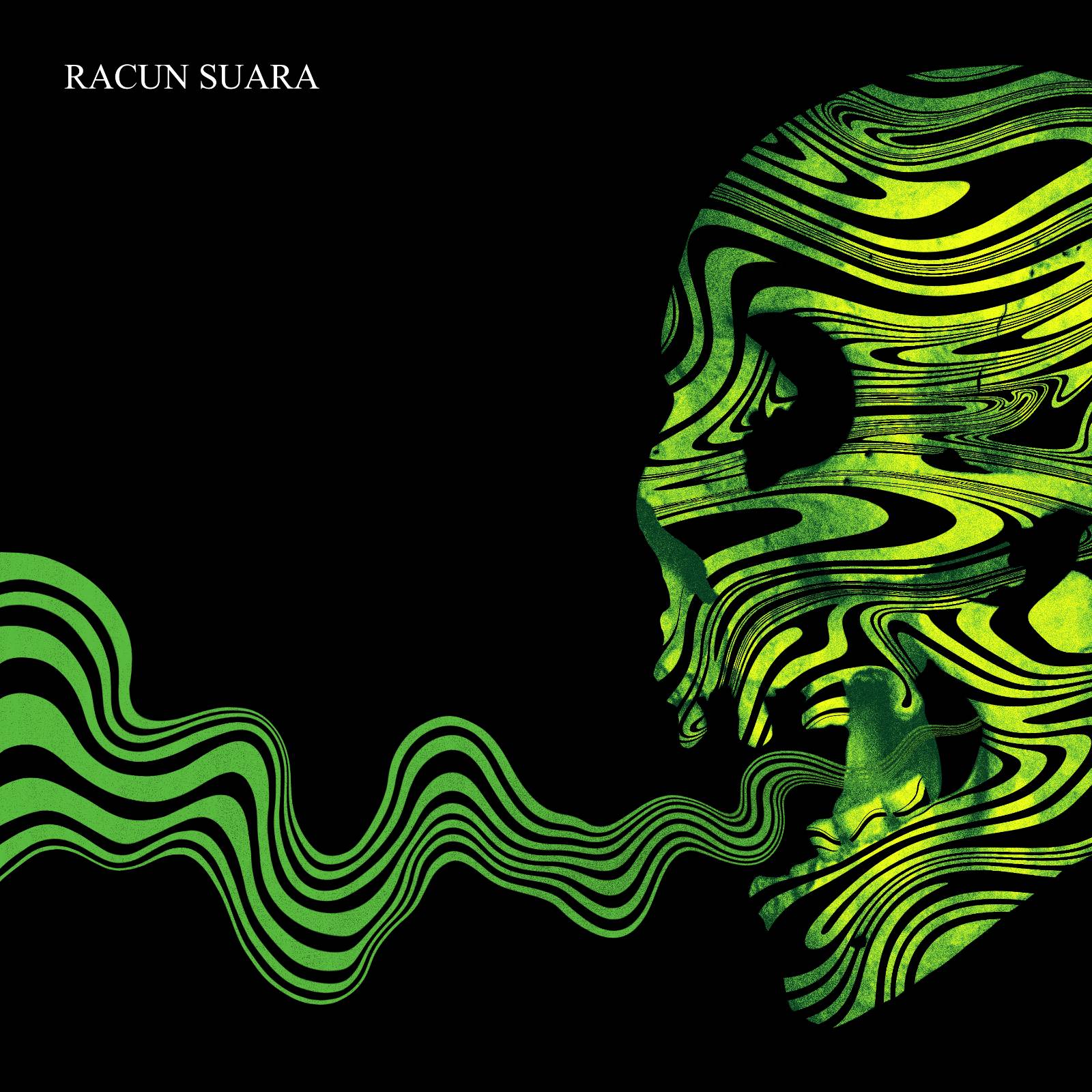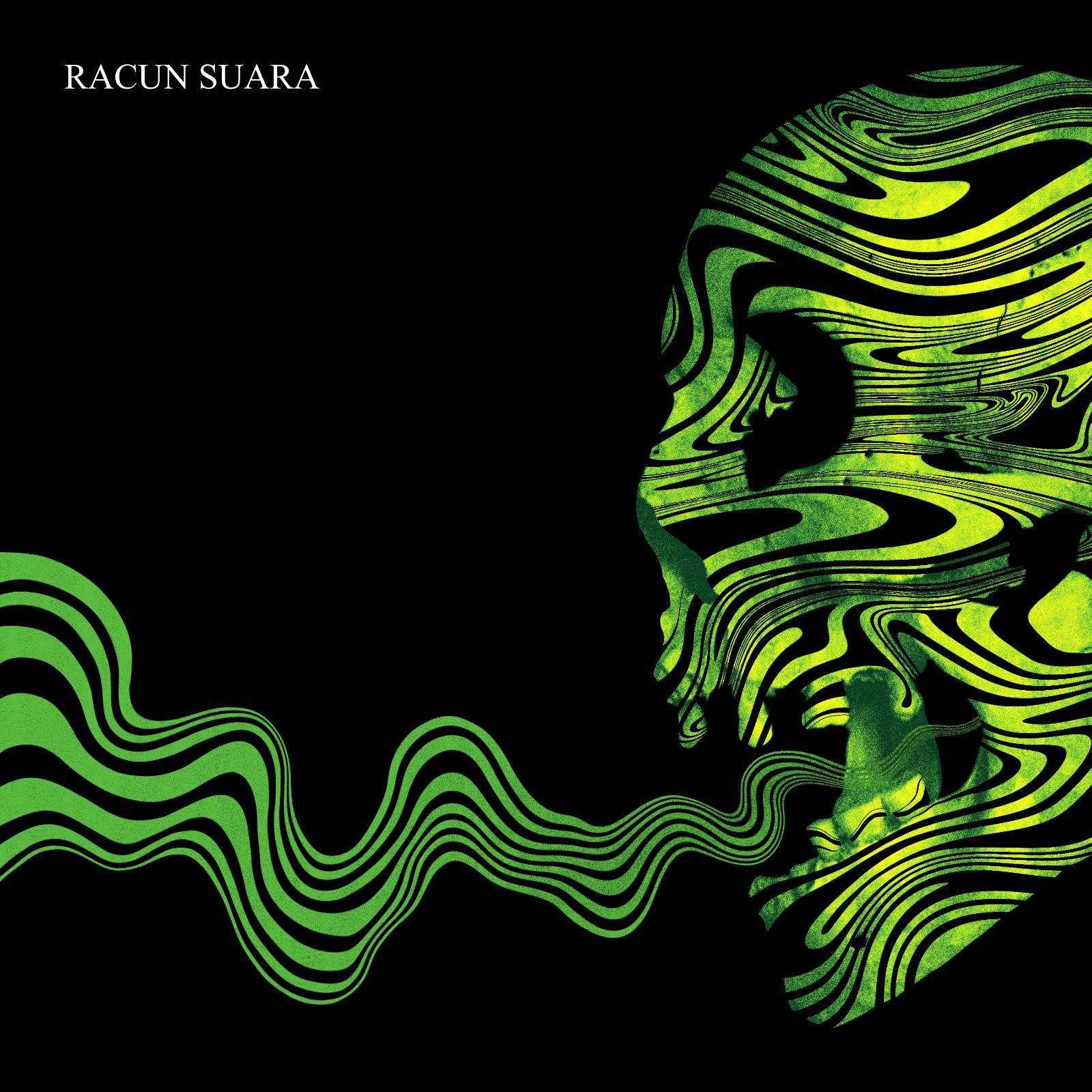Pukulan snare serupa derap sepatu lars yang mendominasi trek Racun Suara dari The Jansen ini tentu akan terngiang di kepala kebanyakan orang selepas mendengarnya. Racun Suara konon ialah respons yang konon hadir atas dominannya kegelapan di situasi sosial politik Indonesia yang bahkan belum genap satu semester dipimpin Prabowo - Gibran. The Jansen secara lugas, gamblang dan sadar memilih ungkapan “trauma dari tentara” untuk menutup reff yang lumrahnya merupakan bagan paling sakral dalam sebuah lagu. Berani dan memang sudah sepatutnya.
#IndonesiaGelap adalah realitas kondisi Negara kita belakangan. Mau secara makro atau mikro, kondisi ekonomi kita cenderung tidak baik-baik saja. Nilai tukar terhadap mata uang kita terhadap dolar Amerika Serikat bahkan sempat menyentuh titik terendah yang lebih buruk dari angka saat krisis moneter menerpa Indonesia di 1998. Sejumlah industri padat karya harus gulung tikar. Masa bulan madu di bisnis startup seolah sudah berakhir. Para pekerja seperti ojek daring harus terus berjibaku sebab kondisi keuangan mereka yang bahkan bisa dikategorikan sebagai pengangguran terselubung. Situasi naas juga harus ditelan para warga yang telah lulus menjalani proses rekrutmen menjadi pegawai pemerintahan. Kiprah dan pemenuhan hak mereka terus mengalami penundaan.
Ujian besar ekonomi juga hadir di dapur pemerintahan. Telinga kita bisa jadi sudah lelah mendengar kata efisiensi. Penurunan kualitas layanan publik harus kita rasakan dengan alibi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis. Tapi tentu kita tidak lengah bahwa efisiensi adalah kamuflase, sebab para pejabat masih bermewah-mewah dan ternyata ada peluncuran program perjudian besar yakni Danantara yang problematik. Dan tunggu, sialnya ini bukan kabar buruk terakhir yang kita dapatkan.
Kita memasuki Maret 2025 yang juga bertepatan dengan Ramadan 1446 H dengan terus berulangnya proses penyelenggaraan kekuasaan yang ugal-ugalan. Lebih brutal ketimbang pukulan cepat hi-hat di kebanyakan lagu The Jansen yang malah tidak kita dapatkan di Racun Suara ini. DPR RI dan Pemerintah hendak merevisi UU 34/2004 alias UU TNI. Urusan legislasi atau penyusunan dan juga pengubahan aturan hukum memang jadi kewenangan DPR RI. Tapi, alasan UU TNI yang dipilih, poin-poin yang ingin diselipkan ke dalamnya hingga bagaimana prosesnya yang tertutup hingga penggunaan akhir pekan dan hotel mewah sekelas Hotel Fairmont di tengah (ya, lagi-lagi) efisiensi membuat kita harus bertanya-tanya.
Situasi ini memang seolah menjadi Normal Yang Baru (meminjam salah satu lagu Efek Rumah Kaca) di Senayan. Gelapnya proses legislasi revisi UU TNI bukanlah contoh pertama. Revisi UU BUMN yang menjadi dasar di balik adanya Danantara hingga contoh segamblang UU Cipta Kerja yang menggunakan teknik Omnibus Law di 2020 bisa dijadikan contoh lainnya. DPR RI kembali memainkan peran antagonisnya terhadap kepentingan warga. Secara sederhana, para politisi yang terpilih lewat proses pemilu ini masih seperti apa yang Iwan Fals gambarkan dalam lagu Surat Buat Wakil Rakyat yang secara terpaksa masih saya jadikan rujukan sebab situasi separah ini.
Lagu Lama Kaset Baru
Nada-nada sumbang terhadap revisi UU TNI bukan muncul di ruang hampa. Walau bisa jadi ada saja orang yang memang berpikir dan merasa benci terhadap institusi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan di Negara kita ini, dan pikiran apalagi perasaan tidak pernah bisa dinilai salah. Kritik dan pandangan kita terhadap kiprah militer di Indonesia selalu sah untuk dikemukakan. Bahkan bisa dianggap sebagai bentuk rasa cinta dan kepedulian kita terhadap tentara, atau kalau bukan ya terhadap negara, atau bahkan kalau kamu tidak cinta keduanya bisa dihitung untuk manusia, yakni sesama kita. Bahkan ke para homo sapiens berseragam loreng-loreng ini.
Nada warga yang dianggap fals salah satunya adalah apa yang oleh The Jansen sebut sebagai trauma dari tentara. Komando operasi serapi apapun tidak bisa menihilkan kenyataan yang dirasakan bangsa ini. Trauma ini serupa memori yang terekam warga Yahudi atas bengisnya Nazi dan fasisme binaan Adolf Hitler di Perang Dunia II. Saking besarnya trauma tersebut, kita bahkan sampai di situasi bahwa mengutuk Israel dan Zionisme atas genosida mereka di Palestina sampai hari ini adalah wujud ekspresi anti-semit karena ada relasi kuat dengan situasi Yahudi sebagai agama mayoritas di Israel. Padahal solidaritas kita terhadap Palestina bukan karena kebencian terhadap Israel apalagi untuk umat Yahudi, melainkan atas kegilaan yang kita saksikan atas kehidupan di Palestina. Sesak dan kesedihan atas penderitaan itu nyata kira rasakan.
Trauma akan tentara di Indonesia secara lengkap terangkum dalam Orde Baru. Fase rezim yang dimulai dengan kejahatan paripurna yang menurut data ABRI sendiri yang disampaikan oleh Sarwo Edhie Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD, unit serupa KOPASSUS di TNI hari ini) sedikitnya menumpas tiga juta warga yang diduga ada keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia dan loyalis Soekarno pasca peristiwa Gerakan Satu Oktober meletus di 1965. Situasi seolah “Soeharto atau mati” itu yang juga menyebabkan ribuan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di luar negeri terpaksa kehilangan kewarganegaraan dan menjalani sisa hidup sebagai eksil yang terputus relasi dengan keluarga dan kerabatnya di dalam negeri.
Trauma serupa juga hadir di bumi Papua, Aceh dan Timor Timur (sejak 1999 menjadi Timor Leste) baik lewat operasi secara resmi atau sembunyi-sembunyi. Trauma dari tentara juga sangat mungkin mengalir dalam diri tiap demonstran yang hanya ingin menggunakan haknya demi melihat Indonesia yang lebih baik yang setidaknya sesuai dengan yang tertulis di UUD 1945 dan Pancasila, konstitusi dan dasar negara kita. Trauma dari demonstran itu wajar muncul sebab pernah ada Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 yang menunjukkan tidak segannya aparat menyudahi hidup warganya sendiri. Atau tak berhenti di trauma atas pembunuhan terhadap demonstran, trauma untuk diculik serupa Wiji Thukul dan belasan warga lainnya dalam bingkai Penghilangan Paksa 1997-1998 juga valid dirasakan. Apalagi, penangkapan sewenang-wenang massa aksi juga terus dilakukan oleh POLRI yang dibungkus dalam kemasan “pengamanan”. Total dalam delapan dekade Negara ini eksis, sedikitnya lima puluh ribu warga diculik oleh aparatnya sendiri.
UU TNI semestinya direvisi dengan poin untuk mencegah kengerian-kengerian serupa terulang. Situasi penegakan hukum terhadap tindak pidana apalagi pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh prajurit hingga komando oleh perwira TNI masih jadi barang langka di Negara yang kabarnya menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terpesona atau Tersepona?
Nada sumbang berikutnya yang bisa disebut sebagai nada dasar sebab menjadi isu utama dari pro-kontra UU TNI adalah apa yang disebut dengan Dwifungsi TNI yang merupakan transformasi dari Dwifungsi ABRI yang juga jadi komponen pokok era Orde Baru. Satu konsepsi yang membuat para prajurit dan perwira TNI bisa terlibat tidak hanya dalam urusan pertahanan melainkan juga dalam banyak sendi kehidupan di tengah-tengah kita. Konsep ini juga kerap disebut sebagai “TNI Berkarya” bak duet maut dengan “Golongan Karya” sebagai penopang utama Dinasti Cendana yang terus mendapat ruang termasuk dengan cara bermesraan dengan Dinasti Mulyono dari Surakarta.
Dalih bahwa Dwifungsi TNI berupa eksistensi TNI aktif di aktivitas politik baik di kekuasaan eksekutif atau legislatif seperti Fraksi ABRI di hari-hari Orde Baru adalah upaya penyempitan medan perang sesungguhnya. Untuk definisi sempit itu saja ada pelanggaran terhadapnya. Faktanya sejumlah perwira TNI dan POLRI aktif yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Daerah di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota saat menunggu masa Pilkada Serentak 2024. Apalagi jika kita memakai definisi lebih luas bahwa Dwifungsi TNI bisa berwujud turut aktifnya mereka dalam kehidupan sosial ekonomi publik secara umum.
Terlalu banyak keluhan warga yang mengalami kesulitan memilih moda transportasi di sejumlah bandar udara sebab pilihan dibatasi monopoli oleh koperasi milik tentara. Kita juga disuguhkan eksistensi mereka di sektor olahraga. Selain aktifnya perwira aktif di sejumlah federasi dan organisasi cabang olahraga, terdapat pula klub sepak bola dengan latar belakang TNI aktif juga di kancah balbalan negara kita.
Klub yang sering disebut sebagai salah satu klub siluman ini bernama PS Tira yang merupakan akronim dari Persatuan Sepakbola Tentara Nasional Indonesia - Rakyat. Klub yang semula eksis sebagai PS TNI ini adalah kanibalisasi atas Persiram Raja Ampat di tahun 2015. Sejarah kemudian mencatat merger mereka dengan Persikabo Kabupaten Bogor sehingga berubah menjadi Persikabo 1973 yang eksis di 2020.
Minimnya (atau mungkin nihil) bentuk kolaborasi seperti chant atau cinderamata dari unit-unit musik indierock andalan Bogor yang akrab disebut sebagai Mang-chester seperti The Kuda, Swellow, Rrag, Texpack hingga The Jansen itu sendiri dengan Persikabo 1973 hari ini bisa menjadi jawaban tersendiri atas contoh dampak relasi aneh sipil yang dikooptasi militer ini. Tidak akan terbayang dalam konteks eratnya pelaku musik dan komunitas sepakbola di banyak kota-kota dunia, kita melihat Edo Wallad, Adipati atau Tata dan Adji menjadi capo untuk memandu sorak sorai supporter di Stadion Pakansari. Dalam situasi Persikabo seperti ini, rasanya akan absurd sekali.
Dominasi militer dalam kehidupan sehari-hari warga seperti dalam musik dan olahraga juga terpampang nyata dari terbatasnya pilihan ruang selain ruang yang secara administrasi berada di bawah penguasaan militer yang memang tersebar di mana-mana. Lapangan dan ruang-ruang yang dikelola tentara kerap menjadi pilihan penyelenggara konser, festival musik, kompetisi sepakbola bahkan dimungkinkan untuk menjadi venue pernikahan kalian juga, bukan?.
Banyak Jalan Kembali ke Barak
Keluhan offside yang menyebabkan jenis pekerjaan para serdadu ini bertambah bahkan juga muncul dari internal mereka. Peran perbantuan untuk makan bergizi gratis hingga program ketahanan pangan seperti food estate bukanlah pilihan yang sesuai dengan identitas kemiliteran. Keluhan muncul dari keresahan paling sederhana yakni bertambahnya beban kerja mereka secara umum.
Ide pengkaryaan prajurit TNI di ranah sipil kerap dimunculkan dengan alibi tingkat kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Argumen contoh pekerjaan sampingan seperti menjadi ojek daring dan tukang sayur bahkan menjadi narasi yang dikedepankan. Tentu ada jurang lebar antara kondisi di atas dengan usulan perluasan area keterlibatan TNI aktif di ranah sipil. Peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh terhadap prajurit tidak bisa hanya dijawab dengan terbukanya peluang perwira-perwira menengah hingga tinggi di TNI untuk mengisi pos-pos sipil. Kesenjangan yang bisa berujung menjadi kecemburuan justru bisa menjadi bara api dalam sekam.
Hal-hal menyangkut hak ketenagakerjaan hingga kesejahteraan para prajurit bahkan juga menjadi perhatian para pegiat masyarakat sipil seperti yang turut diperjuangkan almarhum Munir Said Thalib. Munir berpandangan bahwa jika tidak terpenuhi kesejahteraannya, fokus tentara untuk menjaga pertahanan Negara menjadi terganggu. Ruang penyalahgunaan kewenangan hingga kekuatan menjadi potensi yang tentunya membahayakan. Ketimpangan situasi antara sipil dan militer tentu membuat persaingan di sejumlah aspek termasuk bisnis dan ekonomi menjadi tidak imbang. Mirisnya, UU TNI 34/2004 disahkan tidak lama setelah pembunuhan Munir pada 7 September 2004. Pembunuhan yang belum dituntaskan pencarian keadilannya ini disinyalir kuat melibatkan nama-nama purnawirawan ABRI yang masih dikaryakan dalam dunia intelijen nasional.
Bisingnya kita terhadap revisi UU TNI ini juga sebagian besar berasal dari keinginan akan TNI yang profesional. Bahwa kesuksesan militer di Indonesia dan atau tiap Negara di dunia adalah keberhasilan membuat ranah pertahanan stabil dan kondusif. Dalam keseharian yang membuat fokus TNI terpecah selain untuk urusan pertahanan, kerentanan saat situasi perang atau kondisi genting lainnya tiba menjadi meningkat untuk kita semua. Mencegah lebih baik daripada mengobati tentu menjadi perumpamaan sangat tepat untuk risiko ini.
Jadi, selain secara harfiah para prajurit menghabiskan lebih banyak waktu untuk urusan di markas dan pos-pos berkenaan dengan pertahanan. Frasa kembali ke barak ingin mendudukkan bagaimana seharusnya posisi militer yang baik dalam kehidupan negara yang menganut demokrasi dan hak asasi. Banyak alasan dan kebaikan dari praktik profesionalisme militer dalam skema supremasi sipil a la republik. Meski sialnya kita malah hendak diajak putar balik ke era kegelapan itu.
Apa Mantra Kita untuk Berubah?
Menjalani kehidupan bak orang dewasa membuat kita sadar bahwa mantra “berubah!” serupa Power Rangers favorit kita tidak lantas mengubah keadaan begitu dirapalkan. Perubahan membutuhkan banyak pengorbanan serta percobaan sebab kita bertarung dengan ketidakpastian. Jika ada rumus pasti yang bisa menghadirkan keadilan, kita tak perlu menghabiskan sedikitnya 18 tahun untuk protes di seberang Istana Negara melalui Aksi Kamisan. Mantra secanggih “Revolusi Mental” bahkan jadi memori betapa manipulatifnya proses politik pencitraan hingga berujung pengkhianatan akan konstitusi lewat nepotisme Jokowi untuk Gibran.
Kepala saya (dan semoga kamu juga) berpikir keras bagaimana bisa menembus kebuntuan hidup di Indonesia yang terus Banal Semakin Binal. Mantra “No Viral, No Justice!” menghadirkan ilusi bahwa perubahan bisa menyeruak dari jempol kita di media sosial. Konten menjadi senjata. Beberapa kerusakan bisa kita cegah. Tapi kepala demi kepala yang mendambakan perubahan belum pernah secara jelas menentukan ke mana arah dan dengan apa mereka menuju ke titik tujuannya. Karena ternyata bisa saja viralitas tercipta tapi tanpa kebenaran dan keadilan menyertainya. Terbaru, fitur AI ciptaan X yakni Grok yang bisa menjawab ragam pertanyaan publik terus digunakan untuk mempertanyakan sejumlah hal, termasuk mengenai misteri di balik sejumlah pelanggaran berat HAM di Indonesia. Jawabannya tidak berbeda jauh dengan apa yang banyak pihak seperti KontraS kemukakan bertahun-tahun lamanya. Apakah penegakan hukum terhadap sejumlah masalah tersebut akan berjalan?. Tampaknya, ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian dan jawaban itu sendiri bagi kita.
Mengutip kalimat yang juga kita bisa anggap sebagai mantra yang tersemat di profil akun media sosial Adji Pamungkas (@djinganjingan) bahwa “syair dan chord gitar tak mampu menghilangkan rasa lapar”, Racun Suara apalagi esai berantakan ini juga tak akan cukup menghadirkan perubahan. Pahit dan getirnya, kita juga harus mengakui bahwa hampir segala daya upaya yang kita kerahkan untuk membendung jahatnya pemerintahan, berujung jadi kemenangan yang tertunda.
Tapi tentu respons, sikap, bacot, aksi dan solidaritas kita tetaplah sangat penting. Sangat penting. Tidak mungkin sesuatu yang tergerak dari hati nurani dan akal sehat kita akan kita nihilkan sendiri. Maka mantra lainnya yang sering muncul di situasi ini yakni “Organisir!” bisa jadi adalah salah satu opsi yang kita patut terus coba. Segala teori dan referensi bisa jadi memenuhi ruang-ruang ekspresi di sekeliling kita hari ini. Mari terus berdinamika dengan menguji dan memperkuat satu sama lain. Kejahatan orang-orang bejat ini tak hanya punya tempat pembalasan di neraka, melainkan juga bisa diadili di dunia yang kita hidupi hari ini.
Mantra “sekecil-kecilnya perlawanan adalah perlawanan” tetap harus dirawat sambil kita coba terus perbesar daya dampaknya. Sesederhana upaya The Jansen mengunggah versi unplugged Tipu Daya Sejarah di hari pengesahan UU TNI pada 20 Maret 2025 yang entah berkaitan atau tidak tapi faktanya hari itu juga merupakan hari bertambah usianya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tempat saya beraktivitas sehari-hari selama lima tahun terakhir. Sesingkat mencuit #TolakRUUTNI yang kini bermigrasi menjadi #CabutUUTNI. Seringan turut menyebarluaskan konten atau template add yours mengenai isu ini di Instagram kamu. Selentur The Jansen yang santai saja menambahkan unsur orchestra di lagu ini meski kadung dilekatkan dengan citra Punk 70-an. Hingga seberani kehadiran kamu di aksi massa yang penuh trauma dan risiko tapi tetap kamu tempuh. Semoga kita berkenan untuk terus lakukan. Sebab militerisme sudah secara gamblang hadir di depan pintu rumah kita. Terus coba untuk melawan. Sampai kita mendapatkan mantra dan resep perubahannya. Sampai menang!.
Hadirnya mantra “Represi bukanlah cara kau tuk berekspresi” yang diulang-ulang lebih dari dua menit sekaligus untuk menutup lagu ini semoga setidaknya dapat menghadirkan cakrawala diskursus atas keniscayaan akan kekerasan dalam semesta perlawanan kita. Baik yang memang kerap muncul dari Negara sebagai instrumen utama kekerasan atau yang bisa saja muncul sebagai ekspresi dari pihak-pihak di sekeliling kita. Rantai kekerasan terus memanjang dan seolah bertanya apa tindakan kita berikutnya. Menjelma suara yang meracuni hari-hari kita ke depan.
Menutup liner notes yang panjangnya tidak kalah dari panjangnya durasi Racun Suara, mari kita mengamini mantra yang disusun oleh The Jansen di lagu ini. Mantra yang tidak kalah utopisnya dari mantra andalan “Datang hari tanpa batas. Tanpa Negara tanpa agama.” milik Dongker di trek Bertaruh Pada Api.
Mantra ini berbunyi
“Yang ku harapkan, suatu pagi akan ada hari tanpa trauma dari tentara.”
Ahmad Sajali
Jakarta, 7 April 2025
Artwork Racun Suara oleh Derian Erlangga
Dengar dan unduh Racun Suara dari The Jansen di sini
Tags

KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan