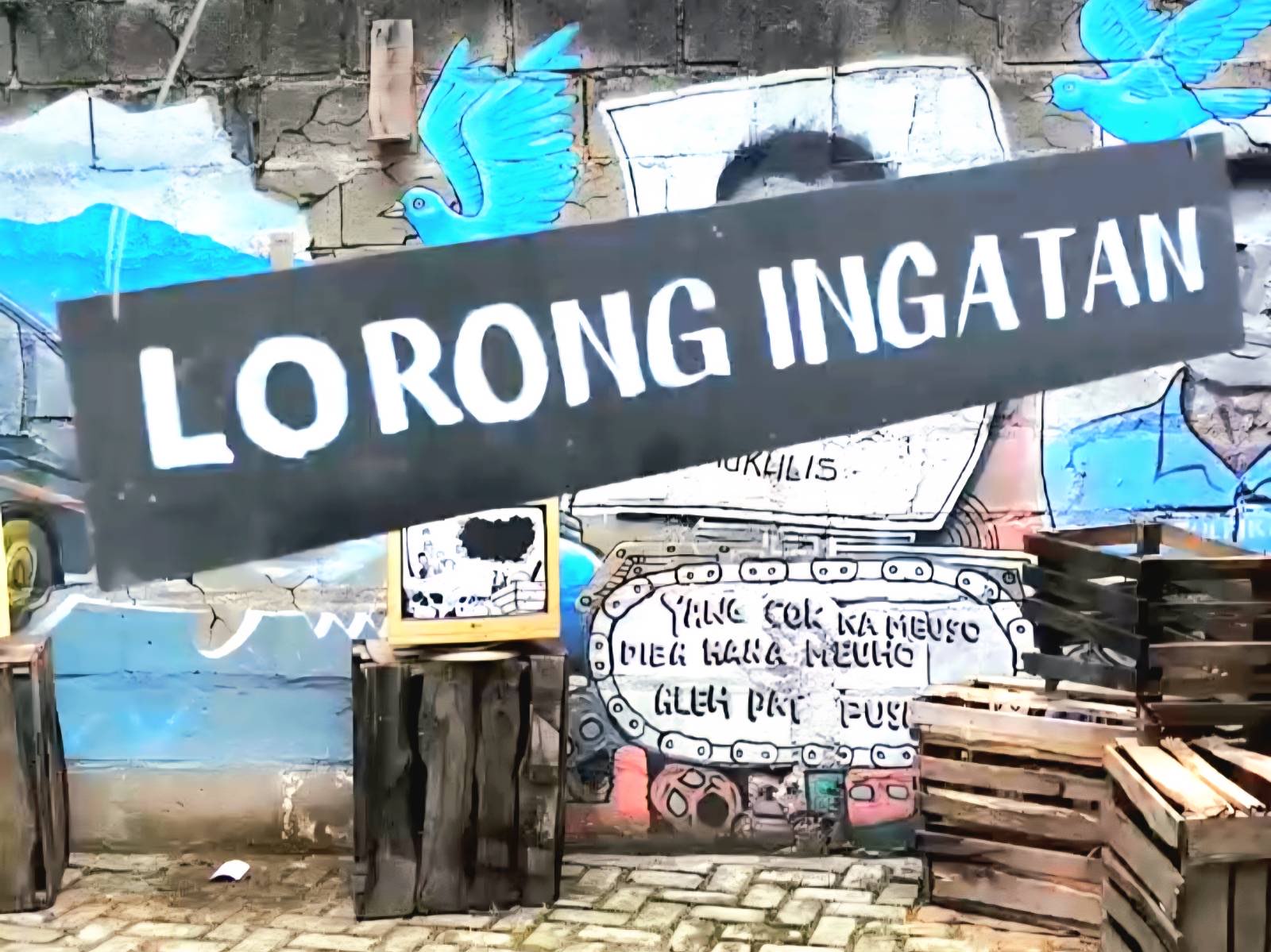Rilis Pers
Dua Dekade MoU Helsinki: Kegagalan Janji Damai, Bangkitnya Militerisasi
15 Agustus 2025 — Hari ini, pada 20 tahun silam, Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menandai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Perjanjian damai ini bukan hanya soal akhir dari konflik bersenjata antara Indonesia dan GAM, melainkan juga akhir dari luka mendalam dan trauma berkepanjangan yang bersemayam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hari penandatanganan MoU Helsinki menjadi peristiwa penting yang memberikan harapan bagi masyarakat Aceh, khususnya para korban, akan keadilan, pemulihan, dan masa depan yang lebih baik.
MoU Helsinki bukan hanya berisi kesepakatan mengenai tata pelaksanaan pemerintahan di Aceh ataupun simbolisasi semata perjanjian damai pada tingkat elit antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Lebih dari itu, MoU Helsinki turut mengamanatkan penuntasan berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama periode konflik dan langkah-langkah binadamai (peacebuilding) pada tingkat masyarakat guna menata kembali kehidupan di Aceh yang damai dan berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM.
Dalam hal ini, MoU Helsinki mengamanatkan: (1) pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh; (2) pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh; (3) demobilisasi militer Indonesia; (4) dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perseorangan; dan (5) kompensasi bagi tahanan politik dan masyarakat sipil yang terkena dampak. MoU Helsinki hadir untuk mewujudkan baik perdamaian negatif—yaitu absennya konflik, maupun perdamaian positif—yaitu struktur yang menciptakan dan merawat perdamaian.
Meski demikian, 20 tahun pasca penandatanganan MoU Helsinki, Pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan pelanggaran berat HAM yang terjadi selama periode 1976–2005. Sesuai dengan isi kesepakatan dari MoU Helsinki, Pemerintah Indonesia—sebagai pemangku kewajiban (duty-bearer) dalam kaitannya dengan HAM, memiliki kewajiban untuk mengungkap kebenaran, menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku, memberikan pemulihan terhadap korban, dan menjamin ketidakberulangan peristiwa. Ketidakseriusan dan minimnya komitmen Pemerintah Indonesia untuk menunaikan keempat kewajiban tersebut membuat perdamaian di Aceh belum sepenuhnya terwujud dan keadilan pun masih hanya menjadi angan-angan bagi para korban. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sejatinya telah mengatur pembentukan Pengadilan HAM di Aceh dan KKR di Aceh, yaitu paling lambat satu tahun sejak UU tersebut diundangkan. Namun, Pengadilan HAM belum juga kunjung dibentuk di Aceh dan KKR Aceh pun baru dibentuk pada 2016 atas dorongan masyarakat sipil, melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh.
Sejak Laporan Temuan KKR Aceh dirilis pada Oktober 2023, rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan dalam laporan tersebut juga belum sepenuhnya dilaksanakan. Misalnya, untuk memberantas impunitas dan mengadili pelaku pelanggaran HAM, KKR Aceh merekomendasikan agar Jaksa Agung segera menindaklanjuti penyelidikan pro-yustisia untuk tiga kasus (Rumoh Geudong, Simpang KKA, dan Jambo Keupok) dan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menindaklanjuti temuan KKR Aceh yang patut diduga sebagai pelanggaran berat HAM, sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Kenyataannya, Jaksa Agung belum kunjung melakukan penyidikan atas empat kasus pelanggaran berat HAM tersebut (ditambah dengan kasus Bener Meriah) dan proses penyelidikan pro-yustisia pelanggaran berat HAM untuk kasus Bumi Flora belum kunjung dirampungkan oleh Komnas HAM.
Pemerintah Indonesia juga belum memberikan pemulihan yang bermartabat kepada para korban. Sebaliknya, pemerintah malah melakukan upaya penyelesaian non-yudisial melalui PPHAM yang pada kenyataannya tidak melibatkan korban serta berpotensi untuk menguatkan impunitas dan menguburkan fakta mengenai pelanggaran HAM yang terjadi.
Baru-baru ini, pada 10 Juli 2025 silam, pemerintah melalui Kementerian HAM meresmikan Living Park di Kabupaten Pidie yang diklaim sebagai bentuk memorialisasi peristiwa Rumoh Geudong dan memberikan pemulihan dalam bentuk materil kepada sejumlah korban. Faktanya, Living Park tersebut dibangun tanpa suara korban, di atas tanah yang masih menyimpan trauma, dan menggantikan bukti adanya pelanggaran HAM menjadi sebuah taman rekreasi.
Temuan dugaan alat bukti berupa tulang belulang korban pada 2024 silam tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Pemberian pemulihan kepada korban dalam kesempatan peresmian tersebut juga bermasalah, lantaran adanya ketidaksesuaian data korban yang dimiliki pemerintah dengan fakta di lapangan. Situasi ini kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan di antara korban dan konflik antara korban dengan PASKA Aceh selaku pendamping.
Selain itu, Pemerintah Indonesia semakin menambah daftar panjang bentuk pengabaian dan hilangnya penghormatan terhadap MoU Helsinki. Nota kesepahaman tersebut mengamanatkan demobilisasi militer Indonesia dan menetapkan jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Namun, militerisasi justru menguat di Aceh pada periode pemerintahan Prabowo-Gibran hari ini. Pada 10 Agustus 2025 silam, Prabowo Subianto baru saja meresmikan sejumlah satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kesempatan upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer. Satuan-satuan tersebut meliputi satu Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan yang berkedudukan di Aceh Tengah serta lima Batalyon Teritorial Pembangunan yang masing-masing berkedudukan di Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Pidie.
Oleh karena itu, kami menuntut adanya:
-
Penghormatan dan implementasi menyeluruh dari Nota Kesepahaman Helsinki oleh Pemerintah Indonesia;
-
Kepastian dan peningkatan jaminan penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan bagi anak-anak korban konflik;
-
Penuntasan pelanggaran berat HAM di Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan transisi, yaitu mengungkap kebenaran, menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku, memberikan korban pemulihan, dan menjamin ketidakberulangan peristiwa;
-
Tindak lanjut penyelidikan pro-yustisia ke tahap penyidikan oleh Jaksa Agung untuk peristiwa Rumoh Geudong, Simpang KKA, Jambo Keupok, dan Bener Meriah;
-
Penetapan peristiwa Bumi Flora sebagai pelanggaran berat HAM dan tindak lanjut temuan KKR Aceh yang diduga sebagai pelanggaran berat HAM oleh Komnas HAM;
-
Pelaksanaan rekomendasi KKR Aceh secara menyeluruh, termasuk memberikan korban pemulihan yang bermartabat dan melibatkan seluruh korban, oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah;
-
Penyelarasan data korban yang akurat dengan realita di lapangan oleh seluruh lembaga negara sehingga tidak ada lagi perbedaan data antara satu sama lain;
-
Memorialisasi peristiwa pelanggaran HAM dan pelanggaran berat HAM di Aceh yang substantif, melibatkan korban, menghargai martabat korban, dan tidak menghilangkan fakta sejarah; dan
-
Demobilisasi militer Indonesia dan menghentikan militerisasi di Provinsi Aceh sesuai dengan Nota Kesepahaman Helsinki.
Banda Aceh/Pidie/Aceh Utara/Jakarta, 15 Agustus 2025
-
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
-
KontraS Aceh
-
PASKA Aceh
-
Forum Komunikasi Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA (FK3T-SP.KKA)
-
Asia Justice and Rights (AJAR)

KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan